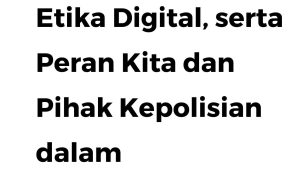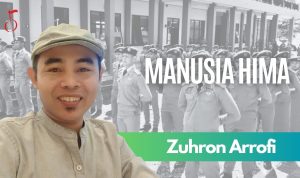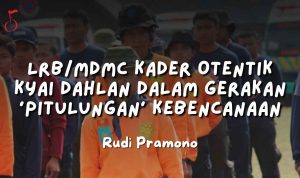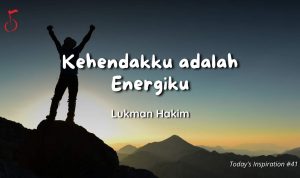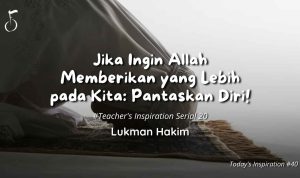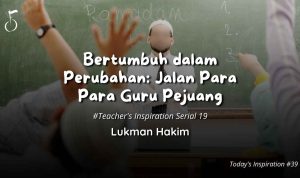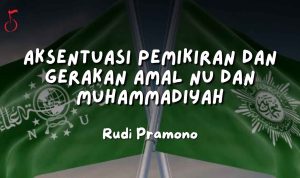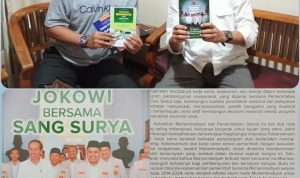Oleh: Achwan Fanani
Satu Percikan
Pada akhir bulan Juni 2022 lalu, PKUB Kemenag RI melakukan Pendidikan Khusus Profesi Mediator di Banda Aceh yang diikuti perwakilan FKUB se-Provinsi Aceh. Dalam salah satu sesi, yaitu Analisis Konflik, ada sesepuh Aceh yang menyampaikan dengan terbuka tentang adanya kemungkinan orang Aceh angkat senjata lagi. Masalahnya adalah salah satu poin kesepakatan Helsinki belum dipenuhi Pemerintah dan DPR, yaitu pengesahan Bendera Aceh. Beliau sudah memulai demonstrasi secara langsung.
Keterbukaan itu tentu kita apresiasi karena itu menunjukkan satu kepercayaan bahwa kita, selaku fasilitator, dipandang sebagai pihak yang punya itikad baik, meskipun kita dari Jawa Tengah. Dalam situasi itu pula, saya berikan pendapat mengenai bagaimana sebaiknya masalah bendera diatasi, yaitu dengan cara evolutif, bukan revolusi yang merugikan rakyat kecil. Ditambah konteks geopolitik yang membuat perjuangan untuk kemudahan diri sangat sulit untuk mendapatkan dukungan internasional saat ini. Selain itu, saya sampaikan bahwa masalah bendera itu cukup sensitif di Jakarta, yang bisa membuat dukungan sebagian kalangan terhadap Pemerintah yang berkuasa melemah.
Setelah beberapa waktu, masalah bendera tidak muncul, tetapi beberapa bulan terakhir, ajakan untuk kembali menggaungkan kemerdekaan Aceh muncul di media sosial. Meski tidak mewakili seluruh masyarakat Aceh, suara-suara itu memantik perdebatan di media aosial hingga memunculkan kembali isu kesukuan dan ras, yang akhir-akhir ini mulai menguat kembali
Menilik Akar Sejarah
Entah bagaimana ceritanya, ketidakpuasan orang Aceh terhadap Pemerintah Pusat kadang diungkapkan sebagai perlawanan terhadap penjajahan Jawa. Karena itu, dalam perjanjian Helsinki Agustus tahun 2005, Yusuf Kalla, tidak menyertakan juru runding dari Jawa. Namun, sebagai sesama muslim, ikatan antara Aceh dengan Jawa tetaplah ada dan masih menjadi salah satu unsur pengikat, karena banyak orang Aceh belajar agama di Jawa maupun orang Jawa di Aceh.
Barangkali persoalan etnisitas ini muncul disebabkan Belanda dahulu mengerahkan pasukan KNIL, yang banyak diisi orang Jawa, saat memadamkan perlawanan Aceh. Meskipun sebenarnya kalangan Uleebalang di Aceh sendiri pada akhirnya menerima kekuasaan Belanda.
Selain itu, orang Aceh selalu mengingat dan mewariskan ingatan tentang pelanggaran janji Soekarno terhadap Daud Beureueh, seorang ulama yang disegani di Aceh, dan kakek Hasan Tiro, inisiator Gerakan Aceh Merdeka. Saat mengajak Aceh bergabung RI, Daud Beureueh mensyaratkan pengakuan pada eksistensi Aceh dan hak untuk menegakkan syariat Islam.
Namun, kemudian hal itu tidak dipenuhi, bahkan Aceh dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara. Hal itu mendorong perlawanan orang Aceh dengan bergabung pada DI/TII, yang berpusat di Jawa Barat pada tahun 1953. Menariknya, meskipun melawan, saat itu Daud Beureueh masih menisnatkan diri pada gerakan Islam yang berkembang di Jawa, yang menunjukkan masih kuatnya kepercayaan kepada hubungan agama terhadap sesama orang Indonesia. Faktor agama (kesatuan umat Islam) ini banyak menjadi kekuatan pengikat ke-Indonesia-an di berbagai wilayah, meski tidak berlaku pula di beberapa wilayah, seperti Balai, Ambon, Sulawesi Utara dan lainnya.
Setelah perlawanan dengan nama DI/TII berhenti di Aceh dengan kesepakatan damai, ternyata ketidakpuasan masih muncul sehingga melahirkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dimotori keturunan Daud Beureueh, yaitu Hasan Tiro. Gerakan GAM ini tidak lagi menjadi agama sebagai isu sentral, tetapi identitas ke-Aceh-an. Gerakan GAM ini direspon Pemerintah Pusat dengan menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dari tahun 1989 sampai tahun 1998, dengan korban yang cukup banyak.
Hal itu mendorong beberapa unsur di GAM mengusahakan penyelesaian secara diplomatik. Tsunami Aceh tahun 2004 menandai satu kesadaran untuk berdamai sebagai satu dorongan keagamaan maupun sosial. Itulah yang membuat perjanjian di Helsinki 15 Agustus 2005, yang menghasilkan kesepakatan damai antara Pemerintah dengan GAM, terwujud.
Perjanjian itu meskipun disambut baik berbagai kalangan, tetapi dipandang kurang menguntungkan oleh beberapa kalangan, baik dari Pemerintah RI maupun dari internal GAM sendiri. Dari masyarakat RI muncul pandangan bahwa perjanjian itu sudah menyalahi doktrin NKRI karena memberi wewenang Aceh, sebagai daerah otonom, untuk punya Partai, Undang-Undang, Wali Nanggroe, Bendera, dan lainnya sehingga muncul candaan bahwa hubungan RI dan Aceh hanya diikat oleh pelabuhan.
Tetapi, bagi sebagian kalangan GAM, perjuangan untuk merdeka itu menjadi kehilangan momentum karena pada akhirnya Aceh tetap di bawah Indonesia. Setelah berjalannya waktu, di internal eks Kombatan sendiri muncul friksi antara mereka yang duduk di pemerintahan dan menikmati akses kekuasaan dengan Kombatan yang kembali ke kampung dan hidup dalam keterbatasan. Muncullah kritik bahwa satu eks panglima GAM tidur di tempat tidur beludru, sedang eks panglima lain hanya tidur di tikar saja.
Persoalan menjadi lebih serius karena pembangunan Aceh tidak seperti yang diharapkan, meskipun Aceh punya kekayaan alam yang besar, seperti cadangan Gas besar di Arun, Aceh Utara. Provinsi Aceh termasuk provinsi yang miskin. Bahkan pasca Pilpres 2014, Pemerintah berkuasa, lebih melihat Indonesia Timur dibandingkan Indonesia Barat sebagai prioritas pembangunan.