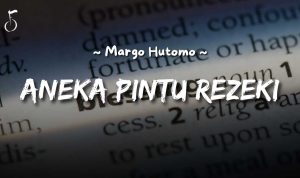Wahyudi Nasution
“Pak Bei, saya mau nggenahke, klarifikasi”, kata Adib sahabat Pak Bei.
“Soal apa, Nda?” tanya Pak Bei.
“Soal acara SASTRA EMHA kemarin”.
Pak Bei tahu sahabatnya itu hadir dan ikut duduk lesehan bersama ratusan penggemar puisi. Dia tampak asyik ngobrol dan “klepas-klepus” (merokok) sambil menikmati minuman SYINI KOPI.
“Sesuai dengan judul acaranya, semua seniman yang tampil ke panggung kemarin membaca puisi Cak Nun tahun 70-an, kecuali Pak Bei.”
“Iya benar,” jawab Pak Bei.
“Kenapa Pak Bei memilih baca Lautan Jilbab? Itu kan puisi Cak Nun tahun 80an.”
“Iya benar.”
Pak Bei maklum, sahabatnya ini memang cukup familiar dengan dunia sastra. Mungkin hanya karena “keblasuk” saja dia dulu tidak kuliah di Fakultas Sastra, tapi di IKIP Negeri yang sekarang jadi UNY, itu pun bukan di jurusan Sastra. Mungkin juga salah pergaulan sehingga dia tidak sempat ikut bergaul di komunitas sastra dan kesenian, padahal tampak minatnya di kesastraan cukup tinggi.
“Puisi-puisi Cak Nun di kumpulan Nyanyian Gelandangan dan M Frustrasi itu kan bagus-bagus, Pak Bei. Syarat kritik sosial. Sangat menggelitik dan kontemplatif. Di puisi-puisi itu Cak Nun seperti memprotes dan mengkritisi keadaan yang terjadi.”
“Iya benar.”
“Ku kira kemarin Pak Bei mau membaca puisi Klembak Menyan. Eeh ternyata malah baca Lautan Jilbab.”
“Begini lho, Nda. Harap dimaklumi, aku ini baru kenal Cak Nun tahun 80an, tepatnya pada 1987 ketika Cak Nun tampil di acara Pentas Seni Ramadhan di Kampus UGM. Waktu itu beliau membacakan satu puisi panjang berjudul LAUTAN JILBAB. Seperti ribuan jamaah yang hadir “tumplek-bleg” di Boulevard UGM waktu itu, aku benar-benar terpesona mendengar puisi itu. Pembacaan Cak Nun sangat indah. Semua penonton seperti tersihir. Luar biasa.”
“Apanya yang luar biasa, Pak Bei?”
“Waktu itu mungkin Sampeyan masih kecil, belum tahu kondisi sosial-politik-budaya-ekonomi yang terjadi di bawah Pemerintah Orde Baru.”
“Iya benar, Pak Bei. Tahun 87 itu saya masih balita.”
“Awal tahun 80an itu masa-masa yang cukup mencekam.”
“Mencekam bagaimana, Pak Bei?”
“Itu awal pemberlakuan sterilisasi kampus dari kegiatan politik, yang dikenal dengan NKK-BKK. Kampus hanya boleh untuk kegiatan belajar. Mahasiswa tidak boleh ngomong politik.”
“Terus, Pak Bei.”
“Tahun 1982 mulai program wajib Penataran P4 bagi seluruh Pegawai Negeri dan Mahasiswa baru. Yang berani mengkritisi akan ditangkap dan dikenakan pasal subversif, dianggap merongrong kewibawaan Pemerintah. Ada yang dituduh antek komunis, dan banyak juga yang dituduh mau mendirikan Negara Islam.”
“Waaah…terus, Pak Bei.”
“Demi stabilitas Pembangunan, tahun 1985 mulai diberlakukan Azas Tunggal. Seluruh organisasi harus berazaskan Pancasila. Yang menolak akan dibekukan, dilarang berkegiatan.”
“Terus…”
“Di tengah situasi pemerintahan militeristik dan represif waktu itu, ternyata justru lahir kesadaran baru di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk lebih bersungguh-sungguh mempelajari ajaran Islam. Di Yogyakarta ada Jamaah Shalahuddin sebagai motor dan pusat kegiatan kreatif mahasiswa Islam, sedangkan di Bandung ada Masjid Salman ITB. Dari kedua pusat kegiatan mahasiswa Islam itulah virus-virus kesadaran kembali ke ajaran Islam menyebar ke seluruh kampus di Tanah Air.”
“Terus apa hubungannya dengan Lautan Jilbab, Pak Bei?”
“Dari kajian-kajian di kedua lembaga itu, lahirlah kesadaran di kalangan pelajar putri dan mahasiswi tentang wajibnya perempuan berjilbab. Satu-dua pelajar dan mahasiswi mulai berani memakai jilbab di sekolah dan kampus.”
“Terus, Pak Bei.”
“Tapi mereka diintimidasi di sekolah atau kampusnya, disuruh melepas jilbab atau kalau tidak mau, mereka akan dikeluarkan. Maka, dulu hampir setiap hari kita baca di koran ada siswa, mahasiswi, dan karyawati kantor dipecat gara-gara berjilbab.”
“Wah sampe segitunya, ya.”
“Iya, Nda. Tapi, meski dalam suasana terintimidasi, ternyata semakin hari justru semakin banyak wanita memakai jilbab. Namanya juga keyakinan, semakin dilarang, orang justru semakin berani menunjukkan keyakinannya, meski dengan segala resiko yang terjadi.”
“Terus, Pak Bei.”
“Nah, situasi itu berhasil direkam dengan baik oleh Cak Nun. Spirit jaman itulah yang dituangkannya pada puisi panjang LAUTAN JILBAB dengan perspektif beliau yang sangat luas dan dalam sehingga mampu menggetarkan jiwa pendengarnya.”
“Bisa kubayangkan, dampak dari pembacaan Lautan Jilbab di UGM waktu itu, yang sudah berjilbab jadi semakin mantap berjilbab, dan yang belum berjilbab jadi mikir-mikir tentang perlunya berjilbab.”
“Dampaknya waktu itu belum seberapa, Nda. Yang lebih dahsyat baru tahun-tahun kemudian, terutama setelah Lautan Jilbab dipentaskan dalam format drama kolosal oleh Sanggar Shalahuddin UGM di Gelanggang Mahasiswa dengan judul Teaterikalisasi Puisi Lautan Jilbab. Pementasan dua malam itu ditonton oleh tidak kurang dari 5.000 orang. Koran-koran pun menulis bahwa pementasan Lautan Jilbab itu telah memecahkan rekor penonton teater di Yogyakarta.”
“Siapa saja tokoh yang terlibat waktu itu, Pak Bei?”
“Ada banyak tokoh yang terlibat. Yang terpenting adalah Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun sebagai penulis naskah. Lalu, ada alm. Agung Waskito sebagai sutradara, ilustrasi musik oleh alm. Sapto Raharjo, dan supervisor alm. Kuntowijoyo.”
“Pemainnya siapa saja, Pak Bei?”
“Waktu itu ada 30an pemain. Mereka mahasiswa/i UGM, IAIN Suka, UII, STIPER, UPN, dan ada juga beberapa yang pegawai dan karyawan toko.”
“Jadi bukan hanya dari UGM, ya?”
“Ya bukan. Jamaah Shalahuddin dulu memang terbuka bagi siapa saja yang berminat belajar keislaman dan dakwah.”
“Terus , Pak Bei…”
“Pementasan yang jadi ‘viral’ itu rupanya bikin banyak orang jadi penasaran.”
“Maksudnya?”
“Tiga bulan kemudian, Sanggar Shalahuddin diundang mementaskan Lautan Jilbab itu di IKIP Malang, 5-6 bulan kemudian diundang pentas di Makassar, lalu berturut-turut pentas di Madiun dan Surabaya. Ahamdulillah, di setiap pementasan itu dihadiri olah puluhan ribu penonton. Itu pementasan teater yang betul-betul luar biasa dari segi estetika, tapi juga dari segi penonton dan dampak ikutannya.”
“Dari nonton pementasan itu orang semakin yakin dan berani berjilbab begitu maksud Pak Bei?”
“Menurut kesaksianku iya, Nda. Itulah makanya, ada ribuan karya puisi Can Nun, tapi menurutku yang paling dahsyat adalah Lautan Jilbab. Puisi ini bukan hanya indah dan enak dibaca, tapi juga telah terbukti mengubah dunia.”
“Mengubah dunia bagaimana maksud Pak Bei?”
“Sebelumnya orang masih takut-takut memakai jilbab, lalu punya keberanian memakai jilbab secara terang-terangan di mana saja dan kapan saja, tanpa ada lagi intimidasi dan larangan dari atasan. Semakin hari semakin banyak wanita berjilbab. Lihat saja sekarang, hampir semua muslimah di negeri ini memakai jilbab. Siswi-siswi di sekolah dan mahasiswi di kampus negeri pun mayoritas memakai jilbab. Di kantor- kantor, muslimah berjibab. Bahkan, di kepolisian dan tentara pun, hampir semua muslimah juga berjilbab. Ini luar biasa, kan?”
“Iya juga, ya. Hebat betul puisi Lautan Jilbab.”
“Nah, jadi sudah paham kan kenapa kemarin aku memilih baca puisi itu?”
“Iya, Pak Bei. Paham. Apalagi Pak Bei waktu itu terlibat langsung di pementasan teater Lautan Jilbab itu, ya.”
“Iya, Nda. Itulah bagian dari sejarah hidupku yang sangat penting. Alhamdulillah.”
“Ya sudah, Pak Bei. Sudah wijang. Sudah jelas semuanya. Saya pamit pulang dulu, ya. Nanti sampai rumah menjelang Shubuh.”
“Terima kasih, Nda. Hati-hati di jalan, ya. Jangan ngantuk.”
Adib langsung meninggalkan nDalem Pak Bei menuju rumahnya di Godean, kota kecil 10 km di sebelah barat kota Yogyakarta. Semoga aman di jalan.
21 Oktober 2023
#KetuaLPUMKM-PDM-Klaten
#MPM-PPMuhammadiyah
#JamaahTaniMuhammadiyah-JATAM