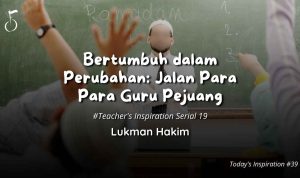Emha Ainun Najib
Fordem.id – Tidak jelas apa bahasa Indonesianya tapi biasa disebut slilit. Kalau habis ditraktir makan sate, biasanya ada serabut kecil sisa daging nyelip diantara gigi-itulah slilit.
Slilit sama sekali tidak penting. Tak pernah jadi urusan nasional. Tak berkaitan dengan setiap kampanye pembangunan. Koran tak pernah meng-cover-nya. Para ilmuwan atau penyair tak pernah mengingatnya. Bahkan satu-satunya produksi ekonomi yang punya urusan dengannya disebut “tusuk gigi”. Padahal slilit-lah yang ditusuk.
Namun begitulah, slilit pernah memusingkan seorang kiai di alam kuburnya, bahkan mengancam kemungkinan suksesnya masuk surga. Ceritanya, dia mendadak dipanggil Tuhan, sebelum para santrinya siap untuk itu. Murid-murid setia itu, sesudah menguburkan sang kiai, lantas nglembur mengaji berhari-hari agar diperkenankan bertemu ruh beliau barang satu dua jenak.
Dan Allah Yang Maha Memungkinkan Segala Kejadian akhirnya menunjukkan tanda kebenaran-Nya dalam mimpi para santri itu. Ruh kiai menemui mereka.
Terjadilah wawancara singkat, perihal nasib sang kiai di “sana”. “Baik-baik, Nak. Dosa-dosaku umumnya diampuni. Amalku diterima. Cuma ada satu hal yang membuatku masygul. Kalian ingat waktu aku memimpin kenduri di rumah pak Kusen? Sehabis makan bareng, hadirin berebut menyalamiku, hingga tak sempat aku mengurus slilit di gigiku.
Ketika pulang, di tengah jalan, barulah bisa kulakukan sesuatu. Karena lupa enggak bawa tusuk slilit, maka aku mengambil potongan kayu kecil dari pagar orang. Kini, alangkah sedihnya : aku lupa minta maaf kepada yang empunya perihal tindakan mencuri itu. Apakah Allah bakal mengampuniku ?”.
Para santri pun turut berduka. Kemudian membayangkan, alangkah lebih malangnya nasib sang Kiai bila slilit di giginya itu, serta tusuk yang dicurinya itu, sebesar gelondongan kayu raksasa di hutan Kalimantan. Lebih-lebih lagi kalau menyamai Hotel Asoka atau Candi Borobudur, setidaknya satelit Palapa.
Ada satu intensitas ruhani tertentu dari hidup manusia. Yakni, tempat Tuhan begitu mutlak. Tempat pahala begitu sakral, dan dosa begitu menakutkan dari Banaspati. Intensitas itu tentunya bergantung pada bagaimana seseorang mengolah dirinya dalam hidup.
Meski demikian, hal itu sebenarnya naluriah saja. Tanpa mengenal konsep dosa secara agama-pun, orang yang menebang pohon angker dan jatuh sakit menganggap penyakitnya karena dosa kepada yang punya dan menjaga pohon itu. Ada juga yang merasionalisasi : karena tindakan penebangan itu merusak sistem ekologis.
Seorang Indian Wintu di California berkata pilu :
“Orang-orang kulit putih itu tak pernah mencintai tanah, rusa atau beruang. Jika kami makan daging, kami tak menyisakannya. Jika kami memerlukan akar, kami bikin lubang bukan mencerabutnya. Kami tak menumbangkan pohon. Kami hanya memakai kayu yang sudah mati.
Tapi, orang kulit putih membajak tanah, merobohkan pohon, membunuh segala yang dikehendaki. Pohon-pohon menangis, ‘Jangan! Aku luka dan sakit’- tapi mereka mencabutnya, memotong- motongnya. Ruh tanah benci mereka! Mereka meledakkan batu-batu, gunung-gunung kecil, menghamparkannya di tanah hingga saling tak bisa bernapas.
Batu-batu mengaduh, ‘Jangan! Aku pecah dan sedih’- tapi mereka tak ambil peduli. Bagaimana ruh batu menyayangi mereka? Apa saja yang tersentuh tangan mereka, rusaklah segala sesuatu itu…!”
Naluri jernih suku Wintu bagai menyindir sejarah, sesudah kepunahan bangsa kulit merah. Manusia dengan kecerdasan berhasil menaklukkan alam, menggenggamnya, mengeksplorasinya, menyulapnya menjadi surga impian, memakannya, menghabiskannya, menguras dan mengenyamnya, demi kelayakan-kelayakan yang irrasional dan mubazir, bagai direncanakan untuk menyegerakan berbagai kehancuran yang ditutup-tutupi.
Jika naluri suku Wintu bisa disebut identik dengan kesadaran dosa, pada zaman serba penaklukkan ini rumusan dosa telah begitu sukar diperoleh. Segalanya serba berkaitan, semrawut dan membenang kusut, menjadi tak begitu penting, juga di negeri yang bangsanya tampak begitu religius.
Kata “Tuhan” disebut ratusan kali setiap hari. Konsep dosa tidak memiliki fungsi di hampir setiap kebijaksanaan yang menyangkut orang banyak. Konsep dosa hanya tersisa di bagian pinggiran dari urusan pokok masyarakat.
Dan di bagian pinggiran itulah hidup pak Kiai, yang sangat masygul akibat dosa slilit-nya.
[ Disadur Fordem.id dari buku : “Slilit Sang Kiai”, karya Emha Ainun Najib, penerbit Pustaka Utama Grafiti, tahun 1992 cetakan ke V ]