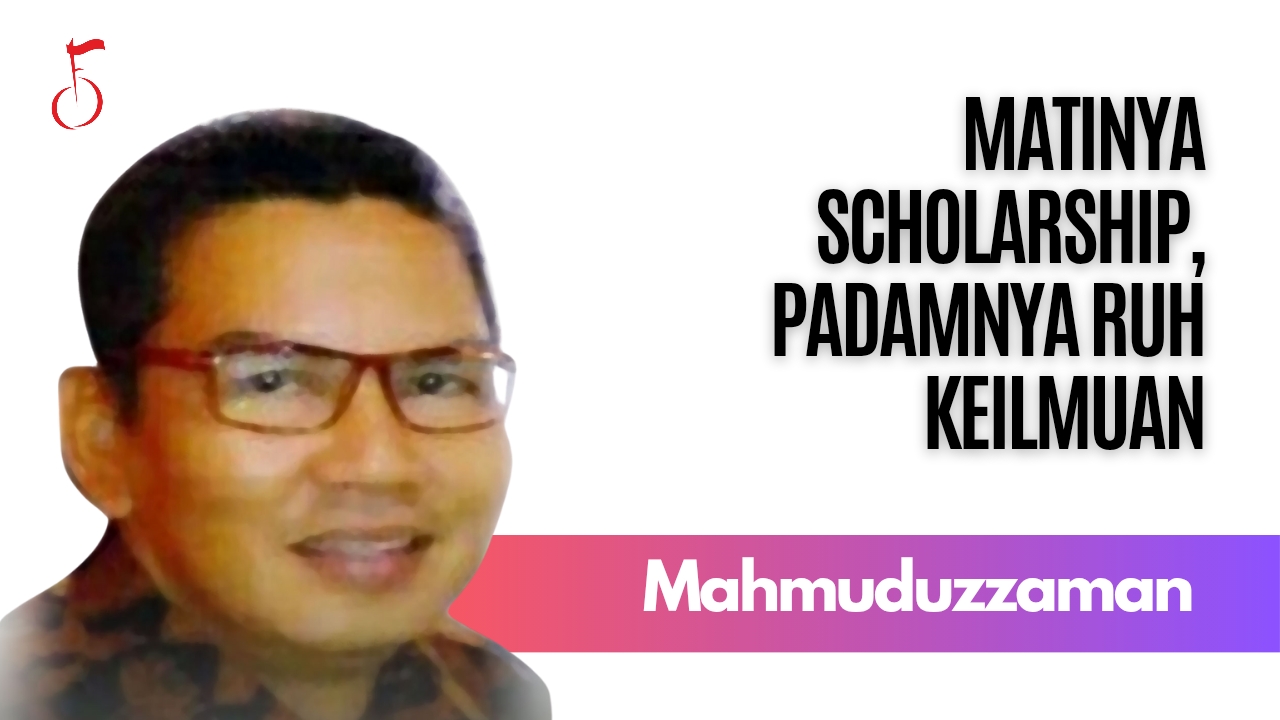Oleh: Mahmuduzzaman (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali, Kordinator Bidang Hukum dan HAM/ LBH-AP)
Fordem.id – Ada sesuatu yang pelan-pelan memudar dari dunia kampus. Bukan gedung, bukan laboratorium, tetapi ruhnya: kejujuran dan ketulusan dalam mencari ilmu. Dalam istilah akademik, orang menyebutnya scholarship.
Dulu, menjadi ilmuwan berarti menjadi penjaga kebenaran. Kini, banyak yang sekadar menjadi pengumpul angka kredit dan penghitung publikasi. Di banyak perguruan tinggi, ilmu bukan lagi jalan menuju kebijaksanaan, melainkan sarana mencapai peringkat.
Mengejar Angka
Kalimat “publish or perish” terbit atau punah kini menjadi semboyan tak resmi dunia kampus. Dosen harus menulis, meneliti, dan menerbitkan sebanyak-banyaknya agar tetap dianggap “hidup” di dunia akademik. Masalahnya, semangat mengejar angka sering mengalahkan semangat mencari makna. Penelitian dilakukan tergesa-gesa. Data diolah agar tampak menarik. Dan tak sedikit yang akhirnya berlabuh di jurnal predator jurnal yang mau menerbitkan apa saja asal dibayar.
Hasilnya? Banyak karya yang lahir tanpa ruh. Artikel memang banyak, tapi substansinya tipis. Seperti ladang yang luas tapi tandus.
Otoritas Ilmu yang Mulai Runtuh
Dulu, masyarakat mendengar dengan hormat ketika ilmuwan berbicara. Kini, suara para ahli sering kalah oleh suara influencer. Dunia digital membuat semua orang bisa merasa pintar. Tom Nichols, penulis buku The Death of Expertise (2024), menyebutnya sebagai masa ketika orang menolak otoritas ilmu pengetahuan. Di media sosial, kebenaran bisa ditentukan oleh siapa yang paling banyak pengikut, bukan oleh siapa yang paling memahami.
Maka tak heran, masyarakat kini mudah ragu terhadap sains. Rekomendasi ahli sering dianggap “kepentingan tertentu.” Di titik ini, scholarship bukan hanya kehilangan pamor, tapi juga kehilangan kepercayaan. Lebih gawat lagi, banyak penelitian yang tak bisa dibuktikan kembali. Dalam istilah ilmiah disebut replication crisis.
Penelitian oleh Hüttel (2024) dan Bogdan (2025) menunjukkan, di bidang psikologi misalnya, lebih dari separuh penelitian gagal direplikasi. Artinya, kesimpulan ilmiah yang kita baca di jurnal belum tentu bisa diulang dengan hasil yang sama. Krisis ini membuat keilmuan modern goyah. Ilmu yang seharusnya menjadi penuntun, justru sering menjadi teka-teki baru.
Kampus Korporasi
Kampus yang seharusnya menjadi taman berpikir kini lebih mirip perusahaan. Semua diukur dengan angka: jumlah publikasi, akreditasi, peringkat dunia. Bidang ilmu yang dianggap “tidak menjual” seperti filsafat, etika, atau pendidikan karakter, tersingkir perlahan. Padahal di sanalah akar moral scholarship tumbuh.
Laporan Scholars at Risk (2025) mencatat, kebebasan akademik juga terancam di banyak negara. Di beberapa kampus, berbicara terlalu jujur bisa berakibat hilangnya jabatan. Akibatnya, banyak akademisi memilih diam. Ilmu kehilangan keberanian, dan keheningan menggantikan kejujuran.
Masyarakat Jauh dari Ilmu
Ketika ilmu kehilangan kejujuran, masyarakat pun kehilangan kepercayaan. Kita melihatnya saat pandemi: teori konspirasi lebih cepat menyebar daripada jurnal ilmiah. Orang lebih percaya video satu menit daripada riset bertahun-tahun. Ilmuwan dianggap elitis, jauh dari realitas. Padahal, scholarship sejati justru lahir dari kepedulian terhadap manusia. Ilmu bukan hanya soal rumus dan data, tetapi juga nurani. Dan ketika nurani hilang, ilmu berubah menjadi mesin tanpa arah.
Meski begitu, harapan belum padam. Di berbagai tempat, muncul gerakan untuk memperbaiki arah. Beberapa universitas mulai menilai dosen berdasarkan dampak sosial, bukan sekadar banyaknya publikasi. Gerakan open science mengajak peneliti membuka data dan metode agar hasil riset bisa diuji siapa pun.
Di Indonesia, semakin banyak peneliti muda yang menulis dengan bahasa publik — di koran, media sosial, dan forum masyarakat. Ini pertanda baik. Ilmu yang terbuka dan komunikatif akan lebih dipercaya dan lebih hidup. Matinya scholarship bukan akhir dari ilmu pengetahuan, melainkan panggilan untuk berbenah. Dunia akademik perlu kembali ke niat dasarnya: mencari kebenaran, bukan sekadar mengejar peringkat.
Ilmu tidak akan mati selama ada orang yang menulis dengan hati, meneliti dengan jujur, dan mengajar dengan kasih. Scholarship hidup di sanubari orang-orang yang percaya bahwa keilmuan sejati adalah ibadah pengabdian untuk kebaikan manusia. Dan mungkin, dari kampus kecil di daerah, dari ruang kuliah yang sederhana, ruh itu akan menyala kembali.